Opini
Sudah Relevankah Pendidikan Kita?

Sumber: mobelos
Oleh: Namikus
Pendidikan secara umum diartikan sebagai proses
transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi lainnya, baik itu dalam hal
praktik maupun gagasan. Jika yang menjadi acuannya adalah pengetahuan, maka
tentu semua orang pasti mengalami apa yang disebut pendidikan. Karena
pengetahuan sendiri diartikan sebagai segala hal yang diketahui, maka tentunya
setiap orang yang sadar dan berinteraksi pasti mengetahui sesuatu—apapun itu.
Setiap manusia pasti pernah mengalami dua tahap
dalam kehidupan, yaitu proses belajar dan proses bekerja.[1] Di
zaman dan tempat manapun pasti manusia mengalami hal ini, pertama belajar—dalam
bidang apapun meski tidak pernah sekolah, manusia purba pun pasti pernah
belajar, misalnya belajar bertani, berburu, atau minimal belajar berinteraksi,
hal ini biasa dilakukan ketika masih kecil. Kemudian ketika dewasa, manusia
akan melalui fase bekerja. Meski pada saat bekerja orang masih bisa belajar,
tetapi pada fase ini jarang orang mau belajar hal baru. Contohnya, seseorang di
usia 40 tahun, yang telah lama menjadi supir, akan berpikir seribu kali untuk
belajar hal baru untuk pekerjaan baru. Hal itu karena di usia 40 tahun secara
psikologis dan peluang, manusia tidak mau hal-hal yang baru.
Dari dasar itulah sebenarnya saya ingin mengatakan
bahwa pendidikan adalah suatu hal yang pasti bagi manusia, bahkan makhluk
hidup. Setiap dari kita yang mewariskan sesuatu ke generasi berikutnya, baik
itu untuk menunjang praktik maupun pemikiran adalah sebuah proses mendidik.
Sekarang ini, karena melihat pentingnya pendidikan sebagai proses transfer pengetahuan, manusia menciptakan suatu sistem formal untuk melakukan proses pendidikan, yang biasanya disebut sekolah. Di Indonesia sendiri, ada yang disebut wajib belajar 12 tahun, agar masyarakat bisa terdidik dan bisa bekerja sebagai aktivitas ekonominya. Namun yang perlu dilihat dan dicermati, proses belajar yang dilakukan harus sesuai dengan tantangan atau hal yang harus dikerjakan. Misalnya, kita tidak bisa belajar caranya membuat lemari, apabila di masa depan manusia tidak akan menggunakan lemari—keahlian kita akan sisa-sia, lebih ditakutkan lagi kita akan menjadi manusia sampah, yang diusia tua takut untuk belajar baru, tetapi tidak bisa menggunakan hasil belajar kita.
Melalui permasalahan ini dan dalam meninjau kembali
kualitas pendidikan di Indonesia, kami merasa tertarik untuk membahas relevansi
pendidikan di Indonesia. Tetapi sebelum kita jauh membahas relevansi, ada satu
hal penting yang perlu kita rumuskan terlebih dahulu, yaitu tentang tujuan
pendidikan itu sendiri. Hal itu disebabkan karena apabila kita ingin mengetahui
relevan tidaknya suatu pendidikan, kita harus tahu terlebih dahulu, untuk apa
pendidikan itu diberikan.
Dari segi sejarah, pendidikan di Indonesia memainkan
peran penting dalam proses perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Melalui politik
etis, yang di dalamnya terdapat elemen edukasi, telah membangkitkan kesadaran
rakyat, yang diwakilkan oleh kaum intelektual untuk bergerak melawan penjajah.
Maka dari sini, bisa kita lihat bahwa tujuan pendidikan di Indonesia yang pertama adalah membangkitkan
kesadaran untuk melawan penindasan.
Salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang
berasal dari keluarga yang peduli juga terhadap pendidikan pribumi, R.A
Kartini, telah merumuskan tujuan daripada pendidikan itu sendiri bagi rakyat
Indonesia. Dua hal penting yang menjadi tujuan R.A Kartini memperjuangkan
pendidikan, terutama untuk kaum wanita yang terdeskriminasi secara sosial
budaya pada waktu itu. R.A Kartini merumuskan dua hal yang menjadi tujuan
pendidikan itu sendiri dalam Notanya yang berjudul Berilah Orang Jawa Pendidikan, 1) wanita sebagai pendidik, agar
menjadi pendidik yang baik 2) para bangsawan,
agar menjadi penguasa yang bijak dalam melindungi kaulanya.[2]
Tujuan pertama menjadi penting, karena wanita
sebagai salah satu bagian dari keluarga memainkan peran penting dalam
sosialisasi ilmu pengetahuan atau bisa disebut sebagai agen utama transfer
pengetahuan. Hal itu tentu relevan dengan yang terjadi sekarang, karena
keluarga sebagai agen sosialisasi utama memainkan peran penting dalam
pendidikan yang menjadi salah satu tugasnya, dan ibu adalah orang yang pertama
sekaligus utama yang melakukan hal itu di banyak kebudayaan yang ada di dunia.
Oleh karena itulah, R.A Kartini mengkhendaki pendidikan untuk perempuan, karena
perempuan sebagai agen sosialisasi harus memiliki kecerdasan intelektual
sekaligus karakter yang baik, untuk tentunya bisa mencetak generasi yang
unggulan pula, yang di mulai dari keluarga.
Kemudian untuk tujuan yang kedua, agar bangsawan
terdidik dan melindungi kaulanya, memiliki relevansi yang sangat besar dengan
keadaan sekarang. Satu film yang mengisahakan oligarki kekuasaan yang bekerja
sama dengan para kapitalis untuk melanggenggkan sebuah perusahaan yang memang
menguntungkan secara finansial tetapi disisi lain merugikan secara sosial dan
lingkungan—film Sexy Killers,
memperlihatkan kepada kita bagaimana bangsawan yang terdidik secara intelektual
tetapi tidak bisa melindungi kaulanya (masyarakat Indonesia). Memang masih
perlu diperdebatkan jumlah keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari Tambang
Batu Bara (pokok pembahasan film Sexy Killers), tetapi kita juga menyaksikan
bagaimana para bangsawan tidak terlalu memedulikan aspek lingkungan dan masalah
sosial yang ditimbulkan, itulah mengapa pendidikan itu diberikan selain untuk
membuat orang terdidik tetapi juga bisa melindungi masyarakat.
Dari berbagai tujuan yang dipaparkan diatas, bisa
kita ambil benang merah, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk
mengsejahterakan dengan konsep keadilan. Tidak bisa kita tapikan bahwa salah
satu tujuan pendidikan itu tentunya adalah kesejahteraan, kita tidak mau orang
miskin kelaparan, kita tidak mau orang harus bekerja dengan jam kerja yang
padat tetapi diupah murah, kita tidak mau orang mengerjakan sesuatu dengan
paksaan—lebih dari itu, kesejahteraan diberikan untuk kebahagiaan, meski
kebahagiaan itu relatif setiap orang, tetapi penderitaan itu mutlak—orang yang
miskin kelaparan mutlak merasakan rasa sakit, meski mencoba bahagia, tetap saja
ia sakit dan kesejahteraan adalah salah satu jalan keluar.
Kemudian untuk konsep keadilan, meski konsep ini
bisa menjadi perdebatan, seperti, keadilan seperti apa yang digunakan, tetapi
saya rasa semua orang sepakat bahwa keadilan hanya bisa dicapai apabila kita
bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan (etika
humanisme).
Lalu kenapa dua konsep ini yang di dengungkan dalam
tulisan ini. Pertama, kita tidak bisa menampikan bahwa kesejahteraan merupakan
salah satu yang bisa membawa manusia bahagia, meski kia berargumen hebat bahwa
kebahagiaan itu tidak diukur dari materi, tetapi apa kita bisa menapikan bahwa
rasa sakit kelaparan hingga kematian. Kemudian konsep keadilan menjadi penting
dalam hal ini, kesejahteraan dianggap baik apabila bisa untuk tidak mengambil
hak orang lain, lebih dari itu juga peduli terhadap orang lain. Misalnya
seorang borjuis yang makan di restoran dengan makanan dan suasana mewah,
menghabiskan satu kali makan malam seharga gaji pegawainya yang makan seadanya,
digaji kecil, dengan jam kerja yang padat, itu tidak adil. Terserah jika Anda
seorang liberal dan percaya bahwa hal itu wajar, karena borjuis lebih cerdas
dalam bekerja, tetap saja penderitaan bagi proletar itu nyata, dan kenapa tidak
diberikan gaji yang sepadan dengan jam kerja yang manusiawi.
Itulah kenapa kesejahteraan harus dibarengi
keadilan, secara sejarah Bangsa Belanda memang sejahtera, Bangsawan Pribumi
memang sejahtera, tetapi banyak rakyat sengsara. Apakah sekarang kita masih
bisa berargumen bahwa kemiskinan mereka karena malas atau cerdasnya Bangsa
Belanda atau Bangsawan Pribumi—tidak, saya tidak suka mengatakan mereka cerdas,
mereka bisa disebut licik atau jika tidak licik tidak punya empati, bagaimana
mungkin kita mau duduk menikmati coklat panas dengan sebuah buku, sementara
tetangga kita menangis menahan rasa lapar. Itulah kenapa mungkin harus kita
sepakati dahulu, bahwa tujuan pendidikan adalah mengsejahterakan dengan konsep
keadilan.
Setelah kita rumuskan bagaiamana tujuan pendidikan
itu sendiri, maka sudah tampak jelas kemana pendidikan kita akan diarahkan. Hal
ini menyangkut relevansi daripada pendidikan. Pendidikan yang baik tentunya
memiliki relevansi di masa yang akan datang, bagaimanapun juga untuk mencapai
kesejahteraah, pendidikan kita yang seakarang harus bisa menjawab tantangan dan
kebutuhan manusia. Tanpa hal itu, seperti yang disebutkan di awal, mungkin saja
kita akan menjadi manusia-manusia sampah yang tidak bisa mengaktualisasikan
diri kita terhadap realitas yang ada.
Berbicara tentang relevansi pendidikan, tentunya
zaman Hindia Belanda memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan
pendidikan di era sekarang. Harari melihat dan menganalisis bahwa pendidikan
zaman dahulu dengan pendidikan di abad 21 memiliki hal yang sangat berbeda. Hal
itu disebabkan karena kebutuhan dan tantangan yang berbeda pula.[3]
Oleh karena itu, kita mungkin saja tidak bisa menggunakan pendidikan era
Kartini atau Ki Hadjar Dewantara di zaman sekarang, meski memang secara
pengajaran masih ada yang relevan, seperti misalnya pendidikan karakter dan
lain-lain.
Pertanyaannya, pendidikan apa yang sudah tidak
relevan sekarang. Harari mengatakan bahwa pendidikan yang hanya mementingkan
transfer ilmu sudah tidak lagi relevan di era sekarang. Dahulu hal ini masih
penting dan relevan, karena akses terhadap pengetahuan itu terbatas, maksud
saya seberapa banyak buku yang bisa diakses pada waktu itu, belum lagi
intervensi yang sangat kuat dari pemerintahan yang otoriter membuat orang
sangat sulit untuk mengakses pengetahuan. Berbeda dengan sekarang, akses
terhadap pengetahuan nyaris sudah tidak terbatas, banyak perpustakaan berbentuk
fisik maupun tidak, jurnal yang terkoneksi internet, atau pengajaran dari
youtube—intinya jika Anda punya akses terhadap internet, sebenarnya untuk
mendapat pengetahuan, kita tidak memiliki batasan. Kemudian, meski masih ada
tindakan pemerintah yang otoriter dalam intervensi konsumsi gagasan
pengetahuan, tetap saja hal ini masih jauh lebih bebas daripada abad-abad
sebelumnya, semuanya ada di genggaman Anda.
Oleh karena itu, sebenarnya di era sekarang, dimana
pengetahuan melimpah dan tak terbatas, kita menghadapi suatu masalah, yaitu fokus
kita yang terbatas, kita tidak lagi bisa membedakan mana informasi yang benar,
mana informasi yang penting, dan mana informasi yang berguna. Itulah pendidikan
yang kita butuhkan sekarang ini, pendidikan transfer ilmu sudah tidak relevan,
maksud saya jika Anda bisa mengerahui apapun yang ada di internet apa bedanya
Anda dengan mesin pencarian google, dan sehebat atau sebanyak apapun Anda tahu,
tidak akan pernah Anda mengalahkan mesin pencarian tersebut.
Kita butuh pengajaran yang mengajarkan kita bagaiamana
memilah mana informasi yang benar dan tidak, mana informasi yang penting dan
berguna. Dan menurut saya itu bisa kita dapatkan dari pendidikan Kritis. Salah
satu sifat kritis adalah mempertanyakan segala hal, di banyaknya informasi yang
ada dan masuk ke kepala kita kita memerlukan pemahan kritis untuk memilah itu
semua. Kemudian untuk menggapai nalar yang kritis, harus dibangun berdasarkan
diskusi yang akan mengembangkan komunikasi yang baik, dengan diskusi setiap
argumen kita akan terasah dan kosakata kita akan bertambah. Lebih dari itu
untuk membangun argumen yang kokoh juga dibutuhkan kreativitas, kembali kita
melihat manfaat dari diskusi itu. Dan pada akhirnya diskusi yang baik akan
menumbuhkan konsensus yang diterima oleh semua orang, konsensus itulah yang
akan membawa kita untuk bergerak dan bekerja bersama.
Prinsip-prinsip itulah yang saya lihat diinginkan
oleh para penggiat pendidikan pedagogi. Mereka merumuskan empat ‘C’ untuk
menjawab tantangan pendidikan di abad 21, yaitu Critical Thinking, Creativity,
Communication, dan, Colaboration.[4] Saya
melihat hal itu bisa digapai dari suasana diskusi kelas, bukan hanya transfer
ilmu pengetahuan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, sejauh mana bangsa kita
menyadari hal ini, apakah kita siap menghadapi tantangan pendidikan di abad 21,
mari kita paparkan lebih lanjut.
Indonesia sudah mengalami 11 kali perombakan
kurikulum, dari mulai tahun 1947-2013.[5]
Hal itu dilakukan sebagai bentuk evaluasi untuk menyesuaikan dengan tantangan
pendidikan di berbagai zaman. Kurikulum yang sekarang kita pakai adalah,
Kurikulum 2013, yang dilatarbelakangi untuk menyesuaikan dengan kompetensi masa
depan, yaitu 1) kemampuan berkomunikasi 2) kemampuan berpikir jernih dan kritis
3) kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan 4) kemampuan
menjadi warga negara yang bertanggung jawab 5) kemampuan untuk mengerti dan
toleran terhadap pandangan yang berbeda 6) kemampuan hidup dalam masyarakat
yang mengglobal 7) memiliki minat luas dalam kehidupan 8) memiliki kesiapan
untuk bekerja 8) memiliki kecerdasan sesuai bakat/minatnya 9) memiliki rasa
tanggung jawab terhadap lingkungan.[6]
Sebenarnya secara sistematis Kurikulum 13 telah memberikan instrumen rekayasa
sosial untuk memenuhi kompetensi tersebut, diantara dua hal penting yang saya
cermati, yaitu pembentukan suasana diskusi di kelas dan pendidikan karakter.
Lalu kembali ke pertanyaan awal, apakah cara itu
relevan? Maka menurut kami hal ini sangat relevan. Ketika pemerintah menerapkan
instrumen untuk merekayasa kelas mejadi lebih aktif dengan diskusi, maka
sebenarnya itu hal yang bagus, karena diatas telah disinggung pula bagaimana
diskusi membentuk sikap empat ‘C’. Tetapi perlu juga dicermati hambatan-hambatan
yang mengiringi hal itu.
Pertama, budaya diskusi di kelas tidak serta merta
akan langsung tercipta di kelas, terutama apabila kita melihat realitas di masyarakat,
terutama di sekolah, ada semacam kekuasaan yang tidak terlihat antara guru dan
murid yang dituangkan dalam budaya sopan santun dalam interaksi diantara
keduanya. Dan itu sebenarnya terkadang menghambat proses diskusi kelas antara
guru dan murid, apalagi jika guru yang sudah mendekati usia pensiun, dimana
pendidikan transfer ilmu yang lama dia gunakan harus misalnya mendapat kritik
dari murid, yang terjadi adalah biasanya kekuasaan guru terhadap murid itu
muncul dalam bentuk diskusi yang timpang.
Hal ini tentunya bisa di debatkan, tetapi disadari
atau tidak sebuah diskusi yang menyenangkan tidak akan pernah terwujud tanpa
adanya pemikiran persamaan dalam hak untuk memberikan informasi. Dan hal itu di
Indonesia cukup sulit, perlu penyesuaian untuk bisa melakukan diskusi yang
egaliter.
Kemudian untuk pendidikan karakter, sebenarnya hal
ini masih terkandung dalam budaya kritis. Apabila kita mempelajari pengetahuan
dalam pendekatan kritis, pengetahuan tidak lagi bebas nilai (tidak memihak),
tetapi pengetahuan itu harus memihak, memihak kepada siapa? Yaitu kepada orang
yang menderita untuk menciptakan keadilan. Hal itu karena awal dari pendidikan
kritis adalah protes terhadap ilmu yang positivis, menjadikan ilmu sebagai alat
kuasa untuk melanggengkan kekuasaan, walaupun melakukan penindasan.
Artinya pendidikan karakter dan pengetahuan kritis
sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan yang di canangkan
R.A Kartini, lebih dari seabad yang lalu. Dimana pengetahuan itu tidak hanya
menjadikan orang terdidik, tetapi lebih dari itu menjadikan manusia yang
melindungi kaulanya (memihak). Dengan pendidikan karakter diharapkan tumbuh
pemimpin-pemimpin yang cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki
kepedulian sosial yang tinggi, hingga tidak hanya mengkayakan yang kaya, lebih
dari itu menciptakan kesejahteraan dengan konsep keadilan, yaitu yang bisa
dinikmati banyak orang.
Akhirnya, kami melihat bahwa pendidikan dengan
Kurikulum 2013 adalah upaya pemerintah untuk menyesuaikan dengan kompetensi
global. Dan menurut kami itu relevan secara tujuan, tetapi kurang secara
implementasi. Karena melihat adanya kekuasaan yang memisahkan antara pengajar
dan siswa dalam menciptakan suatu diskusi, kami kira perlu adanya training untuk guru bisa lebih terbuka
dan berinteraksi secara menyenangkan dengan siswanya, dengan seperti itu
suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, dan proses diskusi dan pendidikan
karakter bisa diterapkan dengan baik.
Lebih dari itu, kami juga menghimbau pemerintah
untuk tidak terlalu melakukan intervensi dalam diskursus yang dilakukan
masyarakat. Perilaku oknum pemerintah yang beberapa waktu ini terjadi seperti
pembakaran buku, atau pembubaran diskusi, saya kira merupakan bentuk
penghilangan diskursus dalam masyarakat, yang akhirnya juga berdampak pada
ketakutannya orang untuk melakukan diskursus.
[1]
Yuval Noah Harari, 21 Adab untuk Abad 21, Globalindo, Manado, 2018, hlm. 287.
[2]
Dri Arbaningsih, Pendidikan dan Kemandirian Wanita dalam Konteks Nota Kartini,
diakses dari https://pusdimafis.blogspot.com/2019/04/pendidikan-dan-kemandirian-wanita-dalam.html,
pada tanggal 1 Mei 2019.
[3]
Opcit.
[4] Ibid.
[5]
Yulaikha Ramadhani, Yang Meresahkan dari Sistem Sekolah Kita, Tirto.id, diakses
dari https://tirto.id/yang-meresahkan-dari-sistem-sekolah-kita-cnSE, pada
tanggal 1 Mei 2019.
[6]
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013,
Jakarta, Januari 2014

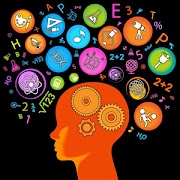

0 Komentar