Cerpen
Pudar
Oleh: Ziera Yolanda
Bagian 1 : Rintik Hujan dan Secangkir Kopi yang Jadi Teman.
Malam ini, hujan kembali menyusuri bumi dengan rintiknya. Dinginnya tak tertahan. Bisingnya, meredam suara apapun di sekitar. Sembari memeluk lengan karena jaket tipis tak mampu menghangatkan, aku mendapati sebuah motor menghampiri. Suara mesin itu tampak familier di pendengaraanku, walaupun dari kejauhan. Dan benar saja, siluet seseorang yang sudah lama tak kujumpa, hadir di hadapanku.
Kau menepikan motor itu, dan bergegas ke arahku. Berteduh. Tak lama, rintik berubah deras, namun tanpa diiringi dengan suara gemuruh yang menegangkan. Seperti déjà vu, aku mendapati kita dalam suasana yang sama, namun dalam keadaan hati yang berbeda.
Kita bergeming dalam sunyinya malam. Saling bertukar pandang dalam diam. Sekali lagi, aku
mengusap lenganku dan merapatkan jaket tipisku. Lalu, kau bersuara, menawarkan aku untuk masuk ke dalam sana.
Kafe Cinta, namanya.
Berjalan aku, mengikuti arahmu. Kita duduk dalam satu angka meja yang sama. Di sudut ruangan, dengan jendela besar yang langsung berhadapan ke jalan. Tak ada obrolan yang terdengar.
Menunduk aku, menautkan jemari dengan gelisah. Mengapa seperti ada jurang pemisah di antara kita? Rasanya, ingin sekali aku meneriakkan kata itu sekencang mungkin kepadamu. Namun lagi-lagi, diamku memenangkan gelisahku. Sampai pesanan kopi kita tiba. Kau membuka suara, kata-kata konyol
yang tak pernah kita ucapkan sewaktu kita bersama. “Gi, apa kabar?”
Menengadah aku, melihatmu yang menyorotku tak terbaca. Wajah teduh itu membuat banyak kilas balik hadir di kepalaku. Namun tak satu pun kata mampu terucap oleh bibirku. Terkunci rapat. Yang kulakukan hanya menyeruput kopi latte kesukaanku. Rasanya... rindu. Mengapa kamu ada, namun terasa berbeda? Mengapa kita harus kembali bersua? Untuk apa?
Menggerutu aku dalam lamunan, sedangkan kamu melihat keluar. Hujan masih setia mengguyur. Dan kau terus melihatnya, mengapa? Apa ingin dia segera pergi? Sama seperti dulu saat aku masih menyukaimu. Tersenyum aku kala mengingatnya kembali. Senyum yang berbanding terbalik dengan rasa bahagia yang pernah kumiliki.
Merogoh saku, aku mencari ponsel untuk memesan taksi online. Rasanya tak sanggup aku berada di sekitarmu lagi. Dengan kau yang kuyakini tak ingin aku kembali. Setibanya taksi itu, tanpa basa-basi aku berlari keluar menghampiri. Tanpa salam perpisahan, seperti yang pernah kau lakukan.
Di dalam taksi yang akan membawa ku pergi, aku tak kuasa lagi menahan diri. Tangis ku pecah usai memikirkan hal lalu yang pernah terjadi, seperti yang sudah-sudah, aku menumpahkan segala sakit hati. Sebelum taksi itu berjalan, aku melihat ke dalam. Kau masih sedia di sana, diam tanpa berniat kemana-mana. Menatap cangkir kopi latte yang sudah tidak ada pemiliknya.
***
Bagian 2 : Sebuah Kelas dan Kakak Kelas.
Semua berawal dari sana, kelas pucat biru muda yang berada di sudut koridor sekolah. Kita ditempatkan dalam satu sudut ruang yang tak terbaca. Mungkin sudah takdirnya, aku ditempatkan satu meja denganmu, yang sebelumnya tak pernah terlihat ada. Kursiku bersebelahan dengan dinding, untuk menggapainya, aku diharuskan melewati kursimu. Selalunya, kau mempersilahkanku lewat tanpa banyak bicara. Dan aku mengucapkan terima kasih tanpa suara.
Engkau, seniorku di sekolah, yang pada awalnya kupikir kau adalah pribadi kaku yang tak banyak bicara. Candamu pun belum terlalu membahana. Seiring berjalannya waktu, kedekatan kita mulai terbentuk, tak ayal perutku sakit kala engkau melontarkan kalimat tawa yang sampai membuatku meneteskan air mata.
Sedekat itu kita, bercanda di atas motor tua milikmu yang turut serta menyumbang bising dan polusi Ibu Kota. Tanpa jarak tak berarti, karena kita sudah saling mengisi. Kedekatan yang terjalin begitu saja, pun diiringi tanpa kejelasan akan siapa kita. Yang kutahu, saat-saat ini begitu indah. Dan yang kupikirkan hanya tetang bahagianya. Tak pernah terlintas, bagaimana bila semuanya berubah.
Ruang kelas pembawa bahagia. Terima kasih engkau telah hadirkan kakak kelas seperti dia.
****
Bagian 3 : Bertemu di Persimpangan Jalan, Kita Saling Menatap Merindukan.
Siang itu, panggung pentas begitu ramai. Lalu lalang orang berjalan menghalangi arah pandangku kepadamu. Dari jauh aku memandangmu yang sedang asyik melihat pentas di panggung itu, ditemani dengan teman-temanmu. Barisan gelak tawa merebak di kelompokmu, dan aku melihat tawamu. Lagi-lagi pemandangan itu tak bosan untuk kutatap, kau selalu sukses membuat bahagia, bahkan hanya dengan melihatmu tertawa. Sampaiku memutuskan tatapku, kau masih belum menyadari keberadaanku.
Pentas terus berjalan, menampilkan pertunjukan komedi yang tak bosan untuk ditonton. Sampai saatnya telah usai, beberapa barisan menanggalkan tempatnya. Membuat lenggang di sekitar. Aku pun berniat meninggalkan tempat itu, rasa haus mulai menghampiriku. Tujuanku kini, membeli sesuatu yang segar untuk menghilangkan dahaga. Berjalan aku menembus beberapa barisan penonton yang masih setia menunggu pertunjukkan selanjutnya. Beberapa kali juga aku tak sengaja ditabrak maupun menabrak. “Maaf, maaf, nggak sengaja kak.” Dan, hanya tatapan sinis yang kuterima. Tanpa mempermasalahkannya, aku berbalik badan ke arah tujuanku semula, dan tanpa kusangka, dirimu berada tepat di depanku. Bagai di drama korea, kau menyambut tatapan terkejutku dengan senyum tampanmu.
“Hai,” sapamu dengan masih menyunggingkan segurat senyum yang kudamba. Aku membalasmu dengan hal yang sama.
Tatapan itu, begitu kurindu. Sudah lama aku tidak melihat tatapan itu dua pekan ini, karena kau yang sedang disibukkan dengan ujian sekolah. Ujian yang akan membawamu melepas status pelajarmu disini. Kau akan pergi. Dan itu membuatku kalut setengah mati. Namun kau berjanji, tak akan ada yang berubah lepas hari ini.
Kembali, kita saling bicara. Duduk di kursi taman sekolah, tempat favorit kita. Saling bertukar cerita, setelah sekian lama tak berjumpa. Kau mengeluhkan semua soal ujian yang susah untuk kau kerjakan, tak lupa pula dengan percobaan contek-menyontek yang gagal kau laksanakan. Tawaku lepas saat kau menampilkan ekspresi kesal yang kau buat-buat. Situasi seperti ini yang enggan membuatku menerima, kalau tak akan lama lagi kau berada di dekatku. Tawaku terinterupsi kenyataan yang akan tiba dengan segera. Wajahku perlahan muram, aku menunduk dengan jemari yang saling menaut. Kau yang menyadari itu, segera tersenyum tipis dan menggenggam tanganku. “Gi, tenang aja. Kita bakal tetep kayak gini. Nggak akan ada yang berubah.”
Kalimat itu yang selalu kau gunakan untuk meredam gelisaku, namun alih-alih padam. Gelisahku berubah menjadi kalimat tanya besar akan sampai kapankah itu? Sampai kapankah kita tidak akan berubah? Apa yang tidak akan berubah? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bersarang di otakku. Sampai saatnya aku bertanya, kau menjawabku dengan mudahnya. Kau menyuruhku ‘tuk datang petang nanti di tempat biasa kita bertemu. Kau berucap semua pertanyaan itu akan kutemukan jawabannya nanti.
Aku menanti petang itu dengan harap cemas. Apakah jawaban yang akan kuterima, akan sesuai dengan ingin dan anganku?Rasanya, semua kisah indah nan bahagia yang kurasakan denganmu, tak ingin sudah seperti ini saja. Kedekatan itu begitu nyata, persis seperti hubungan insan lainnya. Rasanya, tak ada yang lebih indah dari apa yang pernah kurasakan sebelumnya. Walau sebenarnya, serakah rasanya meminta lebih.
Petang itu, akhirnya tiba. Aku datang dengan dress biru langit kesukaanku, juga dengan sepatu putih yang pernah kau belikan waktu itu. Kau pun telah terlihat dari jauh, dengan pakaian casualmu, kau tampak berbeda dari seniorku yang biasa kulihat di sekolah. Aku berniat mendekatimu dengan ringannya. Namun langkahku terhenti begitu saja, kala seorang perempuan cantik ikut menghampirimu dan kau sambut dia dengan senyummu. Interaksi itu, membuatku bungkam. Lidahku kelu, begitu pula dengan respon tubuhku. Mataku terpaku pada satu titik yang masih asyik dengan pertemuan itu. Sampai kau menyadari keberadaanku, kau kenalkan aku tentang siapa perempuan di sampingmu. Kini aku mengerti, akan maksudmu tentang kita yang tidak akan berubah. Karena baru saja, aku mendapatkan jawaban itu secara tidak langsung. Bodohnya, aku baru mengetahui, rupanya di sana kau sudah punya mentarimu sendiri.
****
Bagian 4 : Kita yang Saling, Berubah Asing.
Perkenalan itu begitu singkat. Aku langsung memutuskan untuk pergi dengan alasan ada urusan yang belum aku selesaikan. Setelah hari itu, kau pun tidak terlihat di pandangku lagi. Sekeras apapun aku mencari, kau seperti ditelan bumi. Yang aku ingin saat itu, hanya sebuah kepastian darimu tentang pertanyaanku waktu itu. Namun kini, pertanyaan itu bertambah satu, sudah berakhirkah kita? Tetapi, berakhir pun bukan kata yang tepat, karena sebelumnya pun kita tidak pernah memulai apa-apa.
Hari berganti bulan, lalu berganti tahun. Saat kelulusanku pun tiba, dan aku merayakannya tanpa gairah. Ketidak hadirmu setahun lalu, begitu sulit kurasa. Semua tampak tak berwarna. Meskipun demikian, aku sadar hidupku tidak akan berhenti begitu saja. Sorak sorai tawa bahagia terdengar di telingaku, ajakan berbagai foto kulalui dengan senyuman palsu. Tatapanku pun mengelana pada bangunan sekolah yang tidak akan lagi ku jamah. Semua memori akan apa yang pernah terjadi, hilir berganti terputar kembali.
Semua memori itu pun berubah hanya menjadi sebatas kenangan. Lama aku merenungkan. Sampai sebuah notifikasi pesan yang masuk ke ponselku, membuatku tersadar. Segera aku melihat. Dan setengah tak percaya aku membacanya. Namamu tetera pada si pengirim pesan. Setelah sekian lama kau menghilang, untuk apa sekarang kau hadir mengabarkan?
Ku baca pesanmu lamat-lamat. Tertulis di sana, kau sudah tak berada di kota yang sama. Engkau pun meminta maaf kepadaku, karena pergi begitu saja. Sampai itu saja, aku tak dapat percaya dengan apa yang kubaca, maaf katamu? Untuk apa? Untuk rasa sakit yang kau cipta? Lanjutku membacanya, sialnya, hal selanjutnya justru berkebalikan dengan kata maafmu. Kau menyuruhku untuk melupakanmu, sebab kau telah mengingkari janjimu. Kau membiarkanku untuk membencimu, sebab menurutmu, hanya dengan itulah aku tidak akan terluka lebih dalam lagi. Melupakanmu dengan segera, katamu hal yang baik untuk kita berdua. Tak habis aku percaya, engkau dengan teganya menegaskan aku dengan itu semua. Air mataku untukmu pertama kali jatuh. Waktu itu, aku masih masih tidak percaya. Bahkan sampai hari ini, terkadang aku masih membayangkan itu semua hanya sebuah mimpi.
***
Bagian 5: Semua yang Ku Rasakan Ini, Perlahan Pudar.
Satu hari selepas pertemuan itu, aku terus terbayang kembali dengan apa yang pernah terjadi. Tak pernah satu haripun dalam tiga tahun ini, aku lewati tanpa pernah terlintas di pikiran tetang dirimu. Pintamu waktu itu, belum dapat aku wujudkan, tak pernah berhasil aku laksanakan. Bahkan sampai di saat untuk pertama kalinya kita dipertemukan kembali, rindu yang sempat padam, seketika langsung menguar begitu saja. Rasa benci yang sempat kutanamkan, hilang entah kemana. Yang tersisa hanya ingin melupakan kerenggangan kita, dan kembali seperti dulu kala.
Dalam tiga tahun ini, hanya rasa egois yang kucipta. Aku tak pernah memikirkan bagaimana jiwaku lelah dengan ini semua, bagaimana tangisku sudah tidak bisa mengeluarkan air mata. Aku seakan tak peduli, dan terus melakukan hal yang malah menyakiti diriku sendiri. Salah satu contohnya, ialah berusaha mencari tahu kabarmu lagi. Lewat media sosial aku mencari segala hal yang berhubungan tentangmu. Bahkan tidak hanya dari akun pribadimu, namun dari orang terdekatmu yang kutahu. Sebuah story dengan jam upload yang belum lama dari waktu aku melihatnya, menampilkan sebuah foto bangkar rumah sakit, yang di sana tersemat sebuah kalimat, “Semoga tenang, Dim.” Seketika itu pula, duniaku seakan berhenti berputar, mataku tanpa diminta mengeluarkan airnya yang dua hari ini tidak mau keluar, bibirku bergetar saat otakku berusaha mencerna kata “Dim” di sana. Pikiranku mengelak, hatiku tersayat. Sampai sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak kenal, ku angkat dengan lambat.
Kalimat “halo” yang terucap dengan menahan tangis. Seketika berubah menjadi sebuah gerungan besar bagai suara badai disertai ributnya. Rentetan penjelasan dari suara di ponsel itu, bagaikan alunan mimpi buruk yang lebih buruk dari tiga tahun ini. Kalimat pertama yang bisa kutangkap hanyalah sebuah jawaban atas sangkalanku lima menit yang lalu. Sebuah jawaban yang tidak ingin kudengar, bahkan lebih tak ingin kudengar dari tahun pertama kau meninggalkanku. “Semoga tenang, Dim.” Adalah sebuah pernyataan, bahwa engkau benar-benar telah meninggalkanku seutuhnya. Seutuhnya. Sampai tak pernah ada kesempatanku untuk dipertemukan lagi denganmu.
****
Bagian 6 : Sebuah Surat yang Kau Titipkan.
Untuk Anggita Gantari
Gi, maafin gue yang udah ninggalin lo gitu aja. waktu itu, gue nggak tau lagi harus kayak gimana jelasin ini semua sama lo. saat gue divonis kanker dan umur gue nggak akan lama lagi, hidup gue hancur, Gi. gue harus bergantung sama obat-obatan yang malah membuat gue merasa semakin lemah. kelemahan itu bertambah saat gue melihat lo, dan membayangkan gue harus pergi tinggalin lo. gue hancur saat gue nggak akan bisa tepatin
janji itu sama lo. gue takut liat lo nangis dan berat dengan kepergian gue nanti. jalan satu-satunya yang gue ambil, gue harus pergi gitu aja dari lo. supaya lo bisa benci akan sikap gue ini.
gue pergi ke Australia, bukan karena gue melanjutkan kuliah gue di sana. tapi gue berobat di sana, Gi. Nyokap Bokap gue yang bawa gue ke sana, dengan harapan, sakit gue bisa sembuh. Tapi mungkin, saat lo baca ini, gue udah nggak akan bisa hadir di hadapan lo lagi. udahin semua tangis lo ya, Gi. penuhin permintaan gue tiga tahun lalu. lupain gue, karena ini yang terbaik
untuk kita berdua. lo harus bahagia meski tanpa gue di samping lo. ya, Gi. supaya gue bisa tenang di sana.
satu hal, yang masih ingin gue sampaikan. gue juga sayang sama lo Anggita Gantari. gue suka saat pertama kali kita ketemu. wajah polos dan
imut lo, adalah hal kedua yang membuat gue jatuh hati. hal pertamanya, adalah saat gue tahu lo adalah orang yang udah nolongin gue. saat waktu kecil dipalak sama bocah smp. lo pasti udah lupa itu, cewek tomboy yang langsung teriak ada polisi sampai buat tiga cowok smp lari ketakutan gitu aja. dan lo ketawa lepas sambil nanyain, “kamu nggak papa?” dengan wajah blepotan karena es krim coklat yang lagi lo makan. di saat gue nggak bisa jawab karena asyik nangis, lo malah nawarin es krim yang udah setengah lo jilat. kejadian itu, nggak akan gue lupain. karena lo udah nolongin nyawa gue
dari bocah smp yang sialnya bawa pisau waktu itu. kalau nggak ada lo, udah mati konyol kali gue :)
Anggi, sekali lagi maafin gue ya, yang sampai akhir hayat gue, gue masih menjadi pengecut yang nggak bisa utarain perasaan gue secara
langsung sama lo. saat bertemu lo di kafe ini setelah sekian lama berpisah. gue masih nggak berani nyatain itu. apalagi setelah gue melihat sorot terluka lo yang kentara, membuat gue semakin bimbang.
Gi, lo nggak pernah salah sama gue, jadi lo nggak perlu sesedih itu.
jika lo menyesali kepergian lo di kafe itu, jangan pernah menyesal, Gi. itu semua bukan salah lo. gue yang bikin lo terluka, wajar jika lo masih nggak bisa melihat kehadiran gue. gue pengen lihat lo bahagia, maka dari itu lo nggak boleh terus larut dalam kesedihan. lanjutin hidup lo dengan baik. raih mimpi lo jadi penyanyi hebat yang lo idam-idamkan. jika semua itu berat lo
lakukan, lakukan itu semua demi gue. raih angan lo demi gue, yang nggak akan bisa lagi gue meraih itu semua. janji sama gue Gi, hidup lo bakal baik-baik aja tanpa gue.
:) udah Gi, jangan nangis gitu ah, gue udah pernah bilang ‘kan, muka lo tambah jelek kalo lo nangis. yeeh, malah kejer. udah ah Gi, aus gue, gue mau sleeping handsome dulu yaa.. good bye, Anggita Gantari. i love u..
Dimas.
****
Bagian 7 : Merelakanmu.
Angin sore itu, berhembus lembut, seperti membisikkan sesuatu yang tidak dapat kumengerti akan maksudnya. Aku menyeka kembali setetes air yang meluncur bebas di pipi. Tangisku kini, tanpa suara yang berisik, tidak seperti kemarin. Ia hadir dengan diam yang tenang, namun penuh luka yang menghantam. Dadaku dipenuhi rasa sakit yang membuncah, namun teredam kenyataan janji yang harus kuterima. Di atas gundukan tanah yang dipenuhi bunga, aku bersimpuh dengan rasa tak berdaya. Sepuluh menit sudah orang-orang yang tadi ikut membumikanmu pergi. Namun aku masih setia di sini, enggan untuk kembali. Sebuah surat juga dengan penjelasan seseorang di sini, membuatku semakin bersedih hati.
Kanaya namanya, perempuan yang terakhir kali kulihat bersamamu, sebelum kau pergi
meninggalkanku. Rupanya ia, adalah sepupu jauhmu. Namun cukup akrab denganmu. Saat sore itu, ia sengaja hadir hanya untuk melihat wajahku. Ia berkata, engkau sering menarasikanku sebagai seseorang yang kau sukai. Dan akhirnya, menimbulkan ide konyol terlintas pada pikiran perempuan itu, dirinya
mencoba membuatku cemburu, hanya supaya engkau bisa melihat bahwa aku menyukaimu dan membuatmu menyatakan perasaanmu padaku.
“Nay? Lo ngapain di sini?” / “Ya, gue mau ketemu cewe yang lo sering certain itu lah.” / “Mau ngapain? / “Gue cuma mau kenalan aja sih, yaampun. Udah deh, nggak usah ribet.” / “Tapi, ini nggak tepat waktunya.”
“Di saat itu, Dimas udah ngeliat lo. Jadi dia nggak bisa larang gue terlalu jauh. Saat Dimas ngenalin gue ke elo. Gue tahu Dimas mau bilang kalau gue sepepunya. Tapi, ide konyol itu emang merusak banget. Maaf karena gue udah bilang kalau gue temen deketnya Dimas, bahkan sampai bikin lo nggak bisa ngobrol dengan nyaman sama dia, karena gue terus gangguin Dimas dengan obrolan gue. Saat itu, gue tahu lo pergi bukan karena ada urusan, tapi lo cemburu lihat situasi itu ‘kan? Saat itu gue seneng, karena gue tahu lo suka sama Dimas. Dan cinta Dimas nggak bertepuk sebelah tangan. Tapi setelah kepergian lo itu, Dimas bilang dari awal dia emang nggak merencanakan pertemuan itu buat nyatain perasaannya sama lo. Tapi dia mau ngucapin salam perpisahan, karena dia mau berobat. Dan di saat itu juga, gue baru tahu Dimas sakit. Tapi gue nggak bisa bilang ini semua sama lo, karena Dimas ngelarang, bahkan sebelum gue ngomong mau kasih tahu lo. Dia bilang, dia nggak mau bikin lo kepikiran, cemas, dan takut. Dan dia lebih memilih untuk lo ngebenci dia. Awalnya gue nggak setuju, Gi. Tapi Dimas punya jalan pikirannya sendiri. Lo tahu sendiri, Dimas kayak gimana. Saat setelah empat tahun Dimas di Australia dan nggak ada tanda-tanda dia bakal sembuh. Dimas minta balik aja, dia terus ngerasa kangen sama lo dan ada satu pesan yang mengganjal dihatinya, dan itu harus dia sampaikan secara langsung sama lo. Setelah dua hari dia di Jakarta. Dia memutuskan buat temuin lo di rumah lo. Tapi lo lagi nggak ada, kata nyokap lo, lo lagi hangout sama temen-temen lo. Saat dikasih tahu di mana tempatnya, Dimas langsung susulin lo. Dia bawa motor yang biasa dia pake kalo lagi sama lo, di saat kondisi dia yang masih lemah. Tapi pas sampai di tempat itu, lo udah nggak ada. Tapi Dimas cerita, saat hujan mau turun, dia ngeliat lo lagi berteduh di halte bus. Saat ketemu lo waktu
itu, Dimas pengen.. banget langsung omongin apa yang mau dia sampaikan, tapi katanya berat banget Gi. Sampai akhirnya lo pergi, Dimas tahu kesempatannya udah nggak lama lagi. Dia akhirnya nulis ini buat lo di kafe itu.”
Saat itu, Kanaya langsung memberikan sepucuk surat dengan noda merah di ujung kertasnya. Di kertas itu tersemat tulisan tangan rapi yang sangat aku kenali.
Jika aku tahu, kalau hari itu adalah hari yang paling terakhir untuk kita dapat bertemu, aku tidak akan rela melewatkan satu detik pun untuk tidak memandangimu, berbincang denganmu, dan melepas rindu. Jika aku tahu itu adalah hari terakhir aku melihat wajahmu, maka aku tak akan rela melewatkan satu detik pun untuk tak menunggu kesiapanmu menyatakan perasaanmu padaku.
Hanya kata “jika” yang menjadi pelarianku dan menjadi tempat untukku melempar kesalahan,
namun dalam suratmu aku tidak boleh menyesali itu. Aku harus menuruti semua permintaanmu. Jika dengan aku bahagia dan meraih impianku, kamu dapat tenang di sana. Maka akan aku lakukan. Aku pun akan belajar untuk merelakanmu, meski itu sangat sulit untuk kulakukan.
Perlahan, rintik halus air hujan mulai jatuh ke wajahku, dan aku berniat untuk pergi dari
hadapanmu. Sebelum aku berlalu pergi, aku usap batu nisan bertuliskan namamu, sembari berbisik lihir, “Good bye, Dimas. Semoga.. kamu tenang.” Baru setelahnya, kakiku membawaku pergi meninggalkan tempat peristirahatan terakhirmu. Merelakanmu adalah jalan terakhir yang dapat kutempuh.




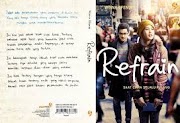
0 Komentar