Ada Apa dengan Perempuan?
Oleh: Puja Ocktaviani
Siang yang sangat terik, entah sudah berapa lama hujan tidak turun, padahal musim kemarau seharusnya belum dimulai. Ruangan kecil dengan kipas tua yang menempel di langit-langit ini, rasanya pengap sekali. Dua orang yang tengah duduk saling berhadapan di ruang ini pun, sesekali menyeka buliran keringat masing-masing.
"Es kelapa kayaknya enak ya?" Wanita setengah baya dengan status sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) itu, mulai memecahkan keheningan di tengah aktivitas berpikir siswi yang belakangan ini tak absen datang ke ruangannya.
"Saya lebih suka es campur." bu Tari, berdecak mendengar respon siswi dengan name tag bernama Anira Putri.
"Kita gak cocok berarti." Kini gantian Anira yang berdecak malas.
"Bu, saya mau konsultasi bukan mau ngebayangin yang segar-segar," Ucapnya. Lantas bu Tari kembali memasang raut seriusnya.
"Ya sudah, jadi gimana? Kamu mau ambil jurusan apa? Sudah mantap yang kemarin? Mau ambil di Universitas itu?" Pertanyaan bertubi-tubi itu berhasil membuat Anira menghela nafas berat.
"Satu-satu ibu." Anira menatap bu Tari frustasi.
"Saya sudah mantap dengan keputusan kemarin, hanya saja... saya belum bicara sama ibu dan ayah." bu Tari mengangguk kecil.
"Sebenarnya resikonya besar nira, sekolah kita tidak pernah ada yang berhasil masuk universitas tersebut, tapi kalau kamu sudah mantap... kita coba, ibu bantu bicara sama ibu ayahmu." Anira terdiam sebelum berakhir mengangguk setuju. Dalam hati ia mulai meneguhkan pendirian, semoga tak ada satupun yang berhasil menghalangi langkahnya. Termasuk restu keluarga untuk melanjutkan pendidikan.
Anira paham, doa dan restu keluarga adalah yang utama. Melihat tak ada satupun anggota keluarga besarnya yang melanjutkan ke jenjang tinggi, mungkin ia akan dihadapkan oleh dua kemungkinan. Antara direstui karena rasa bangga, atau tidak karena dirasa tak perlu. Untuk kesekian kali hari ini, Anira menghela nafas.
"Jadi kamu mau daftar kapan? Besok sudah hari terakhir."
"Malam ini," Ucapnya ditengah keraguan.
Sore harinya Anira pulang menjelang maghrib. Mendekati masa ujian sekolah membuatnya sering pulang terlambat. Seperti hari ini, selepas pulang sekolah Anira pergi bersama teman-temannya untuk mengerjakan dan membahas soal-soal ujian bersama. Karena Anira adalah sosok yang cukup bisa diandalkan, ia selalu di minta untuk menjadi tutor teman sebaya. Anira sendiri tak keberatan untuk itu.
"Kamu ini anak perawan pulang mau maghrib terus, gak baik." Neneknya yang siap pergi ke mushola dekat rumah memandang tak suka.
"Nira habis belajar bareng tadi nek," Ucapnya sambil menyalami neneknya.
"Belajar terus." Anira terdiam, neneknya memang selalu seperti itu, tak ada yang perlu diambil hati.
Dalam rumah sederhana ini, dihuni oleh lima orang. Anira adalah anak pertama dari dua bersaudara, adiknya laki-laki yang menjadi anak kebanggaan dirumah ini. Cucu tersayang yang selalu dinomor satukan. Tak perlu cemburu, memang bukan hal baru jika anak laki-laki lebih dicintai. Anira tak tau diluar sana sama atau tidak, yang jelas di desa tempat tinggalnya ini, budaya patriarki kental sekali.
Rutinitas malam hari Anira setelah makan malam adalah membantu nenek dan ibunya merapikan barang dagangan. Neneknya memiliki kios pakaian muslim wanita di pasar, ibunya pun ikut membantu sehari-hari. Selagi ia membantu, ayahnya sibuk menonton pertandingan bola di televisi. Sedangkan Adiknya entah pergi kemana malam ini.
Sebenarnya Anira tengah dirundung kegelisahan saat ini. Ia sudah janji pada bu Tari untuk mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) malam ini, mengingat besok adalah hari terakhir. Tapi Anira belum juga meminta izin kedua orang tuanya. Ia selalu berusaha mencari waktu yang tepat, namun sampai saat ini nyalinya ciut sendiri. Ia harus menyiapkan banyak jawaban dengan hati yang lapang jika saat ia meminta restu diterpa banyak pertanyaan hingga keputusan yang diambil orang tuanya.
"Itu sih kinan baru pulang?" Anira yang sibuk dengan isi kepalanya tersadar mengikuti arah pandang neneknya yang duduk di ambang pintu rumah. Anira bisa melihat sosok Kinanti, anak tetangga depan rumahnya yang berbeda umur 3 tahun lebih tua darinya.
"Perempuan kok baru pulang jam segini, jam berapa sekarang? Hampir setengah sepuluh malam loh." Lila, ibunya yang sibuk menyusun baju-baju muslim itu menggeleng pelan mendengar ucapan neneknya.
Kinanti kan kerja di kota bu, jauh perjalannya." Neneknya berdecak malas.
"Sejauh apa sih? Suamimu kan juga kerja di kota, tapi gak selarut ini pulangnya." Sungguh, Anira malas sekali mendengar ucapan neneknya. Entah mengapa pandangannya selalu buruk mengenai perempuan yang pulang malam. Seakan-akan pulang malam sudah menggambarkan perempuan tersebut tidak baik.
"Orang tuanya harus menasehati itu, gak baik perempuan pulang malam kalau ada apa-apa yang buruk gimana? Apalagi kalau udah berhubungan dengan laki-laki." Anira menghela nafas kasar. Ia sudah lelah menyanggah ucapan neneknya, mau berapa kali ia memberikan pengertian pun hasilnya tetap sama.
"Oh iya Anira... nenek mau ngomong sesuatu." Anira menghentikan aktivitasnya yang tengah memasukkan hijab-hijab baru.
"Apa?" Entah mengapa ada harap-harap cemas dalam hatinya.
"Nenek mau kamu nikah sama anaknya pak ustad Ali." Tau bagaimana dunia Anira setelah kalimat itu diucapkan? Sunyi sekali. Anira tak mampu mencerna ucapan neneknya, isi kepalanya bahkan mendadak kosong.
"Ibu yang benar aja, Anira kan baru mau lulus sekolah." Ucapan tidak terima ibunya adalah yang pertama kali ia dengar.
"Loh memangnya kenapa? Lagi pula di desa ini menikah muda kan sudah biasa, kamu saja dulu menikah dengan anakku di usia 18 tahun." Nada suara neneknya tak mau kalah.
"Yaa gak bisa disamain loh bu, dulu dan sekarang itu kan beda." Ayahnya ikut mengambil suara, mungkin pertandingan bola sudah tak lagi menarik perhatiannya.
"Tidak ada yang beda, seharusnya semakin maju zaman ini, semakin kamu hati-hati dengan pergaulan anak mu. Kalau menikah kan sudah pasti terhindar dari zina, apalagi husain itu anak ustadz... sholeh dan santun anaknya." Sungguh pusing sekali kepala Anira. Bahkan perdebatan kedua orang tuanya dan neneknya lagi-lagi tak berhasil ia dengar. Ia hanya sibuk memejamkan mata sambil mengatur nafas.
"Anira gak mau, nira mau kuliah di Ibu kota." Kini tiga orang dewasa tersebut membisu ditempat.
"Anira sudah mikirin ini semua dari dulu, impian anira itu kuliah bukan nikah setelah lulus," Ucapnya sambil menahan tangis. Entahlah ia juga bingung sendiri kenapa harus menangis.
"Kuliah itu buat apa nira? Kamu ini perempuan, tugasmu itu ya seperti ibumu nantinya... urus suami dan anak, jangan mencoba jadi anak pembangkang, nenek tau yang terbaik buat kamu." Ingin rasanya ia tertawa keras sekarang.
"Nira," Panggil ayahnya. "Ayah tau kamu gak mau menikah muda, ayah juga gak setuju tentang itu... Tapi rasanya untuk kuliah? Sepertinya tidak usah nak, keluarga kita bukan orang mampu... Lulus SMA saja udah cukup baik." Ternyata kemungkinan yang terpilih adalah, kuliah dianggap tidak perlu. Sejak awal keluarganya memang tak terlalu peduli dengan segala pencapaian yang berhasil ia raih. Sejak awal memang tak ada rasa bangga padanya. Sejak awal memang anak perempuan dianggap tidak perlu menomorsatukan pendidikan. Tapi Amira sudah bertekad, ia ingin merubah segala pandangan rendah tentang perempuan. Terlebih pandangan neneknya.
Anira tak menyangka jika waktu dimana ia meminta restu melanjutkan pendidikan seperti ini. Ia juga tak menyangka jika neneknya berkeinginan untuk menikahinya dengan anak ustadz desa ini. Anira kira semua akan mudah, namun nyatanya jauh lebih rumit dari yang ia kira.
"Ayahmu ini cuma tukang bersih-bersih di kota Anira, apa yang kamu harapkan?
Uang dari mana kalau mau kuliah?" Anira menggigit bibir bawahnya kuat.
"Uang bisa dicari bu, kita gak bisa mematahkan semangat anak gitu aja." Mendengar ucapan ibunya, mata Anira berkaca-kaca.
Lila tersenyum menatap putrinya. "Ibu dukung kamu, ibu tau anak ibu hebat." Lantas air mata yang sedari tadi ditahan, luruh begitu saja.
"Kamu mau jual apa Lila? Punya uang banyak kamu buat sekolahkan anakmu tinggi-tinggi?" Neneknya sudah terlihat emosi sendiri.
"Masih ada anakmu yang laki-laki, pendidikan untuk anak laki-laki itu perlu karena akan menafkahi anak istrinya nanti. Susah-susah kamu sekolahin anak perempuanmu, suatu saat dia pasti dibawa suaminya setelah menikah, kamu dapat apa memang?" Anira sudah tak sanggup lagi. Susah payah ia bangkit dari duduknya. Rasanya sakit sekali mendengar ucapan neneknya.
"Kalau nira boleh jujur, nira gak perlu izin dari nenek buat masa depan nira. Ini hidup nira, gak ada satupun yang berhak atas hidup nira. Nenek bilang apa tadi? Pendidikan buat anak perempuan gak perlu karena suatu saat akan dibawa suami setelah menikah? Nenek salah," Suara Anira mulai tersendat-sendat menahan emosinya.
"Nenek pikir hidup seorang perempuan itu cuma berputar sama laki-laki aja? Nenek pikir dengan menikah dan menghindari zina itu sudah selesai gitu aja? Nggak nek. Kita gak ada yang tau kehidupan setelah menikah itu kaya gimana, apalagi atas dasar paksaan. Perempuan gak bisa cuma bergantung sama suami nek. Kita gak ada yang tahu takdir akan seperti apa kedepannya. Entah diambil tuhan atau diambil perempuan lain. Setidaknya dengan istri yang berpendidikan, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Walaupun suatu saat memilih jadi ibu rumah tangga, istri dan ibu yang berpendidikan itu berbeda. Gak akan ada rasa takut jika suatu saat hal buruk terjadi seperti suaminya meninggal atau direbut perempuan lain." Sepanjang kalimatnya terucap, tak ada satupun dari orang tua ataupun neneknya menyela. Anira tak tahu apa yang diucapkannya jelas atau tidak karena sambil menangis. Tapi ia cukup merasa lega.
"Anira keberatan sama ucapan nenek... dan nira minta maaf, kalau ucapan nira salah atau menyakiti nenek. Nira minta maaf sama ibu dan ayah, kalau nira udah gak tau diri punya mimpi tinggi." Setelah menyelesaikan kalimat menyesakkan itu, Anira masuk kedalam kamarnya. Ia menangis, tak peduli bagaimana suara tangisnya terdengar. Rasanya sudah sangat sakit dibedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Rasanya juga luar biasa sakit, ketika impian yang selama ini ia impikan dianggap tidak penting.
Sebenarnya ada apa dengan perempuan? Mengapa selalu saja ada pembatas dalam kehidupan. Dunia memang sudah maju, namun pemikiran kolot seperti nenek Anira masih kerap ditemukan. Perempuan tak perlu berpendidikan tinggi, perempuan akan berakhir di dapur, perempuan hanya boleh mengurus anak dan suami, perempuan tidak boleh pulang malam, dan peraturan tak tertulis lainnya mengenai perempuan. Padahal ibu Kartini sudah mati-matian menjunjung emansipasi wanita, namun tetap saja tidak semua orang bisa mengerti.
Anira tak tau berapa lama ia menangis sampai tertidur. Matanya jelas membengkak di pagi hari. Untung saja hari ini hari libur, Anira tak perlu berusaha baik-baik saja di sekolah dan menjawab pertanyaan siapapun mengenai matanya yang bengkak karena menangis semalaman.
Perihal pendaftaran, tinggal menghitung jam sampai akhirnya benar-benar ditutup. Subuh-subuh sekali setelah melaksanakan sholat, Anira membuka laman pendaftaran. Ia belum mengantongi restu selain dukungan kecil yang diberikan ibunya semalam.
Mengingatnya, mata Anira kembali berkaca-kaca, ia ingin kembali menangis namun sudah tak bertenaga. Anira sudah mengisi segala hal yang diperlukan untuk pendaftaran. Ia hanya perlu mengklik saja hingga statusnya berhasil terdaftar dalam seleksi. Tapi belum sempat ia mengklik, pintu kamarnya diketuk.
"Nira ibu boleh masuk?" Anira tak langsung menjawab. Namun ia sadar, tidak seharusnya ia bersikap egois seperti ini, mengurung diri di dalam kamar karena keinginannya terhalang.
"Iya bu," Jawabnya. Pintu kamarnya terbuka, menampilkan sosok Lila yang terlihat masih cantik di usianya. Lila tersenyum kecil sebelum benar-benar masuk kedalam kamar.
Anira dan duduk disebelahnya. "Jadi gimana? Kamu sudah daftar? Sebenarnya ibu sudah tau kalau kamu mau lanjut dari bu Tari... beliau hubungi ibu kemarin sore." Anira hampir lupa, guru BK-nya itu memang berjanji untuk membantu meminta izin.
"Ibu keberatan gak? Nira ragu karena ayah sama nenek gak setuju." Lila merangkul putrinya, mengelus punggung Anira lembut.
"Ibu gak keberatan, ibu dukung kamu seratus persen. Kalau ayah-"
"Gak setuju ya bu?" Lila tersenyum tipis.
"Awalnya, tapi ayah bilang setelah sholat subuh tadi... ayah setuju, ayah bahkan lebih semangat kerja karena tau impian kamu." Setetes air mata kembali membasahi pipi Anira.
"Ibu sama ayah yakin, rezeki itu datang dari mana aja. Ibu sama ayah juga bangga sekali sama kamu, kami selalu mendoakan yang terbaik buat anak-anak." Anira lantas memeluk erat ibunya.
"Makasih bu." Isakkan kecil keluar dari bibirnya.
"Gak usah bilang makasih, kamu hanya perlu mewujudkan mimpi kamu." Anira melepaskan pelukannya.
"Ibu sama ayah gak perlu khawatir, nira udah daftar beasiswa dari pemerintah... nira hanya perlu lolos seleksi dan mengurus berkas-berkas. Kalau semuanya berhasil, nira bisa kuliah tanpa biaya sedikitpun." Lila kembali membawa putrinya ke dalam dekapan.
"Ibu tahu anak perempuan ibu hebat, ibu bangga sama kamu nak."
Pagi itu, suasana hati Anira membaik. Ia berhasil mendaftarkan diri dan berhasil mendapat restu kedua orang tuanya. Namun perihal hubungannya dengan sang nenek memang belum membaik. Neneknya tak mau bicara padanya, Anira tak tau sampai kapan namun rasa sakit dihatinya masih cukup membekas. Ia tidak marah, hanya saja susah lupa.
Setelah beberapa minggu berlalu, tibalah saat pengumuman itu datang. Semalaman suntuk ia tidak bisa tidur karena perasaan takut menghujani. Ayah dan ibunya tak henti-henti memanjatkan doa, hal ini semakin membuatnya ketakutan jika berakhir tak lolos seleksi. Ekspektasi kedua orang tuanya sudah tinggi sekali, sedangkan hubungannya dengan neneknya belum membaik. Jika berakhir tidak lolos, entah bagaimana kelanjutan mimpinya.
"Tarik nafas dulu, terus doa lagi baru buka," Ucap ayahnya. Saat ini Anira, adik, ayah, dan ibunya tengah berkumpul di ruang tengah menunggu ia membuka hasil pengumuman.
Rasanya gelisah luar biasa, entah sudah berapa kali Anira menengak air untuk menghilangkan kecemasannya.
"Adek aja deh yang buka." Arya, adiknya mengambil alih ponsel Anira. Sedangkan yang punya hanya pasrah saja.
"Bu, bacain nomor pesertanya." Ibunya lantas bergegas, menyebutkan satu persatu nomor.
"Gimana? Udah kamu klik ar?" Tanya ayahnya. Anira menatap Arya lamat-lamat, entah mengapa anak itu terdiam menatap layar ponselnya.
"Gak lolos ya?" Tanya Anira cemas. Namun Arya justru berdecak.
"Gak seru, masa mba nira jadi ke jakarta sih!" Arya memberikan ponsel Anira pada ibunya. Sontak saja Lila memeluk putrinya erat, menciumnya dengan sayang.
"Kamu berhasil." Ucapan pelan itu berhasil membuat Anira menangis, ayahnya bahkan langsung mendekapnya kuat.
"Anak ayah kuliah." Arya yang melihat pemandangan itu ikut meneteskan air mata. Ia terharu dan ikut merasa bangga. Anira berhasil diterima di salah satu Universitas bergengsi di Jakarta dengan jurusan impiannya, Psikologi.
Hari-hari Anira setelahnya luar biasa indah, ujian sekolah pun telah usai. Ia hanya tinggal menunggu perpisahan sekolah yang akan diadakan besok, lalu bersiap untuk pergi merantau ke Jakarta nantinya. Untuk hari ini ia pulang siang setelah menyelesaikan beberapa persiapan untuk perpisahan besok. Saat sampai di depan rumah, Anira bingung sendiri melihat motor yang biasa dikendarai nenek dan ibunya ke pasar terparkir di sana.
Masuk kedalam rumah, indra penciuman Anira menangkap sesuatu yang sangat menggugah selera. Dengan langkah pelan tapi pasti, Anira menuju ke dapur rumahnya. Penampakan pertama yang berhasil tertangkap matanya adalah ibu dan neneknya yang sibuk menata masakan kedalam kotak nasi.
"Ada acara apa nek?" Alih-alih bertanya pada ibunya, Anira justru bertanya pada neneknya. Entahlah ia merasa harus segera memperbaiki hubungannya dengan neneknya.
"Acara apalagi menurutmu?" Anira menggeleng tak tau.
"Syukuran cucu nenek yang berhasil kuliah, ini nasi kuning spesial untuk berbagi kebahagiaan." Anira terdiam, ia sempat menatap ibunya yang tengah tersenyum manis.
"Nenek gak marah lagi sama nira?" Takut-takut Anira bertanya.
"Nenek gak marah, justru kamu yang marahin nenek. Karena kamu marahin... akhirnya nenek sadar, gak seharusnya nenek bicara seperti itu." Anira tak tau ingin merespon apa, yang bisa ia lakukan adalah mendekati neneknya dan memeluk erat sambil menghujani kata terima kasih.
"Selamat ya sudah jadi anak kuliahan... nikah sama husain nya nanti-nanti aja gapapa." Anira merengut.
"Ihh nenek!" Nenek dan ibunya tertawa.
"Bercanda."
Jadi begitulah kisah Anira dalam mendapatkan restu melanjutkan pendidikannya. Bagaimana usaha kecilnya dalam meyakinkan keluarganya untuk merubah pandangan mengenai perempuan. Budaya patriarki di negeri ini memang sulit sekali dihilangkan, namun tidak ada salahnya untuk sesekali melawan atau sekedar membuktikan jika anak perempuan juga memiliki impian dan layak untuk mewujudkan. Perjalanan Anira memang belum selesai, langkahnya justru baru dimulai.




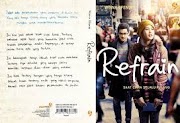
0 Komentar